Merajut Dialog Tanpa Amarah
(dipublikasi di Harian Seputar Indonesia, Minggu 25 Mei 2008)
Kita mungkin tak menyadari bahwa marah merupakan perilaku yang searti dengan peribahasa “sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Bahkan, bisa jadi kita tak mahfum bahwa marah laiknya sebuah wabah penyakit yang bisa menyebar dengan cepat. Setidaknya, itulah dua persoalan yang dikemukakan oleh Carl Semmelroth dalam lembar-lembar awal buku ini.
Marah akan terjadi manakala perilaku orang lain tak sesuai dengan harapan kita. Awalnya, mungkin sekadar meluap dalam bentuk ucapan. Namun lambat-laun kemarahan kita akan mewujud melalui tindakan dengan alasan ‘memberi pelajaran’. Semmelroth mengatakan bahwa kemarahan—sejak pertama kali muncul dalam rasio kita—kepada orang lain memang bertujuan pada tindakan. Marah yang direfleksikan dalam bentuk selain tindakan bagai ‘tabungan’ untuk kemarahan yang lebih besar.
Buku ini sejatinya hanya membahas hubungan orangtua dan anak dalam keluarga. Semmelroth melihat bahwa perilaku marah akan diperkenalkan kepada individu pertama kali oleh anggota keluarga. Hal ini senada dengan analisa Emile Durkheim, yaitu keluarga merupakan media sosialisasi perdana bagi individu. Saat seorang anak sering dimarahi oleh orangtua, sesungguhnya si anak sedang ditularkan ‘penyakit akut’ yang akan membuatnya mudah marah kepada orang lain.
Keluarga memegang peran penting dalam membentuk anggota masyarakat yang sabar dan menjunjung tinggi jalur nir-kekerasan. Oleh karena itu, buku ini juga membawa pesan sosial yang lebih luas cakupannya.
Semmelroth menekankan perlunya pembiasaan diri bagi individu—yang dimulai dari keluarga—untuk melakukan konsensus secara bersama. Hal ini penting untuk menghindari kemarahan orangtua kepada anak. Aturan dalam keluarga haruslah dibentuk dengan jalan urun-rembug antara orangtua dan anak pada ‘satu meja’. Keluhan dan keinginan tiap pihak bisa diutarakan secara bebas dalam momen tersebut.
Lebih jauh, konsensus yang bersemangat egaliter dilakukan agar terbentuk interaksi yang harmonis. Keluarga seharusnya mengajarkan bahwa orangtua bukanlah penguasa bagi anak-anaknya. Interaksi nan egaliter dan terbuka niscaya memberi pengetahuan kepada anak-anak bahwa orangtua pun bisa salah. Kemudian, orangtua bisa memberi contoh kepada anak-anaknya dalam menghadapi kesalahan secara ‘ksatria’.
Orangtua yang pemarah akan membangun kesan ‘angker’ bagi anak-anaknya. Hingga komunikasi antara keduanya bisa terputus. Anak-anak pun tak nyaman dan mudah terjerumus ke dalam perilaku negatif di luar rumah.
Buku ini dilengkapi dengan halaman-halaman yang bisa kita tuliskan untuk mengukur perilaku kemarahan. Semmelroth benar-benar membuat buku terapi dimana pembaca adalah seorang terapis sekaligus pasien. Kemarahan hanya bisa dikurangi bahkan dihilangkan oleh individu yang secara sungguh-sungguh menjauhi perilaku negatif itu.
Semmelroth juga mengungkapkan bahwa ada pula marah yang bermuatan positif. Yaitu ketika seorang anak tidak mematuhi aturan yang dibuat bersama orangtua. Dalam buku ini, Semmelroth mengajari kita teknik memarahi anak yang tidak melukai jiwa dan raga. Malah, menurut saya, tips unik dari Semmelroth tersebut bisa membuat si anak tidak sadar jika sedang dimarahi. Sebuah langkah untuk marah yang menggelitik dan mendidik.
Melalui buku ini, Semmelroth seolah ingin menegaskan bahwa tiap manusia memiliki aura positif yang sebanding dengan aura negatif. Kemarahan yang terlampau sering diterima oleh individu hanya akan membangkitkan aura negatif dan membunuh aura positif dalam dirinya. Lebih jauh, saya melihat bahwa Semmleroth ingin menghadirkan kembali fungsi-fungsi utama dalam keluarga yang saat ini mulai meluntur sebagai akibat dari ‘sapuan badai modernisme’.
Jamak paham, kini orangtua juga sibuk diluar rumah karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, tak selaiknya masalah pelik dalam pekerjaan dibawa orangtua saat berinteraksi dengan anak hingga marah seringkali menyeruak. Melalui buku ini pula, kita diperlihatkan cara menjadikan rumah sebagai wahana yang menyenangkan bagi orangtua dan anak.***



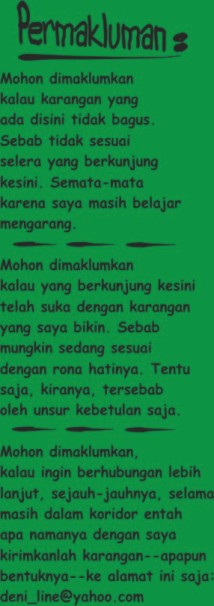


Tidak ada komentar:
Posting Komentar