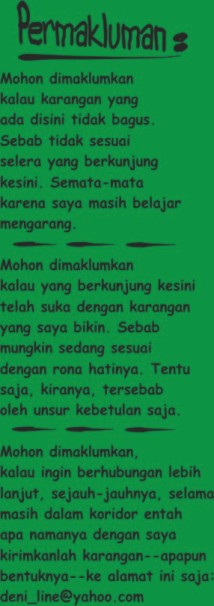Sekeping Pasundan; Serumpun Kisah Cinta
“Selamat Datang”, Leuwi Panjang menyambutku
dengan tantangan sejumput gerimis tipis.
“Maaf”, kataku, ”Aku lupa mencatat berapa kali
dua kaki ini mendekam disini”.
“Tak apa”, balasmu, “Terlalu sering, orang alpa
mengingat telah kemana mereka melangkah”
ingatanku membaca lagi lembarnya yang lusuh;
dulu disini ada pemuda durhaka tersebab cinta.
perahu tertangkup di gunung itulah buktinya.
“Benar”, suaramu menggema tiba-tiba.
“Hei, dilarang menguping”, sahutku, “Aku ingin
bicara dengan hatiku”.
“Ah, dasar penggumam”, cetusmu, “Peduli amat
dengan hatimu. Hati-hatilah dengan hatimu”.
“Kau harus tahu. Aku seperti ini
agar tak durhaka dengan hati sendiri”.
pernah jua, disini, seorang pemuda
menulis puisi cinta yang sungguh panjangnya
memuji elok dan permai nusantara.
2 hari berikutnya, pemuda itu, turut mengucap
3 butir sumpah beraroma menolak tua.
“Aduh sebenarnya kau ini siapa;
Pencinta, Penyair atau Pencatat Sejarah?”, tanyamu menggebu.
“Huh, bagiku tiap orang adalah penyair
hanya saja, kadang mereka malas membuat hatinya mengalir”.
tibatiba, semerbak Cinta Pitaloka mampir juga
di memoriku. Putri itu betapa teguh cintanya.
Jauh sebelum lahir: berputih tulang itu lebih baik
daripada mata yang diputihkan, Sang Putri
dengan bulat keyakinan memberi bukti.
“Sebenarnya sukumu apa?”, tanyamu dengan raut serius.
“Aku hanya searus tubuh yang ingin luruh
menyelami tiap kisah cinta
diseluruh kolam yang menganga”, jawabku lirih.
kini Jatinangor memelukku lagi.
Lalu manis sekali ia bertanya padaku:
“Kisah Cinta apa yang ingin kau dengar
dari harum tanahku ini?”
“Aku ingin mendengar kisah tentang Cinta
yang tetap turun kala lelap menyandera mata”.
Jatinangor; Oktober 2007
yang sekarang nanti terkatakan lampau
merdu suara yang pasti menjelma parau
dekap rindu perlahan jadi jemput kematian
hangat tatapan yang berbayang dingin kebencian
tangan yang berjabat kelak dipakai membabat
kanan pun cepat berlari menuju kepalan kiri
kaki-kaki gerak serempak lalu saling sepak
cinta terserak dipungut berganti sepi paling kabut
oh, sulit sungguh kubaca beda warna pada tubuhmu.
dibubuhkan denyya ketika 21.43 2 tanggapan
Cemas
kau datang lagi
menarinari tak peduli
di pelupuk mata kanan dan kiri.
pun dendangmu terngiang
memajang riang di hati nan usang.
kau tak pernah sekalipun lekang.
ombak tak lelah menggoyang perahu
angin ikut pula berhembus tak semilir
kau tampak tak pernah mau tahu
menggotongku tak henti ke hulu dan hilir
kapan kau akan angkat kaki?
padahal kini telah kumengerti
cemas, sungguh, tak lebih dari mimpi
yang selalu gagal berkemas menuju pagi
Jatinangor; Oktober 2007
dibubuhkan denyya ketika 21.18 0 tanggapan
Resume Wawancara Dengan Penyair dan Puisi
lalu para penyair itu membuat kereta puisi
untuk berjalan diatas tubuhnya
yang telah menjelma rel dengan ikhlasnya
terus saja
deretan gerbong lari menderu
aku bayangkan tetesan airmata
cucuran keringat, ceceran darah
alirmengalir tak henti di
sekujur molek rel
kemudian dengan pelan dan pasti
kereta puisi melesat tinggi
meninggalkan penyair yang jadi rel
menempel sendirian di tanah ini
puisi pasti pergi
sebab ia tahu
penyair akan ditarik kembali
tanpa menenteng puisi
Metro, saat mudik 2007
dibubuhkan denyya ketika 05.16 0 tanggapan

ibu kita tak pernah berhenti
melahirkan anak
melalui kakinya
setelah mampu melangkah
ke kaki ibu tujuan kita
seperti hari ini,
sehabis terbang ke bulan
kaki ibu tak bosan
menunggu disimpuh
Metro; 2007
dibubuhkan denyya ketika 02.38 0 tanggapan
Sebuah Kenangan
Dalam Kereta Ke Selatan Lagi
: Paksi Marga
kita belum kalah
kita belum kalah
angin belum menjelma badai
badan ini hanya butuh
membungkuk sejenak
dan
kepala kita hanya perlu
merunduk sebentar
kita tidak memutar arah
karena kita belum kalah
alir sungai belum lagi beku
deru udara pun tak jua kaku
selama pandang masih setajam panah
yakinlah; kita tak pernah bisa kalah
Jember-Jatinangor-Metro; Oktober 2007
dibubuhkan denyya ketika 02.34 0 tanggapan
Dalam Perjalanan Pulang
Awal Oktober lalu, saya dengan gigih...sebagaimana banyak orang lainnya...bersusah payah pulang kampung alias mudik. Dari Jember...dengan kereta yang berganti dua kali di Surabaya...ke Jatinangor lalu menembus Jakarta...lagi-lagi dengan kereta. Kemudian bermukim sebentar di Gambir...menunggu bis Damri...akhirnya perjalanan panjang lagi ke Metro. Sedikit puisi saya tulis ketika itu. "Anak-anak" saya yang lahir di jalan p(ul)(anj)ang awal Oktober 2007 itu adalah:
Mudik (1)
maka pikirkanlah berapa berat uang,
kalau tubuh ini bisa kembali ke ranjang.
dan hitunglah—kalau kau bisa—
sejauh mana kuat melangkah,
jika angan mampu berlari pergi tak sudah.
Mudik (2)
lalu kereta terus berdenyut
sampaikan pesan yang kalahkan
kemeroncong dalam perut
kemudian peron kembali berdesak
kabarkan kisah yang lagukan
rindu rumah hati sesak
Mudik (3)
para penyair itu
—beruntunglah—
hati mereka
tak pernah henti
diajak kembali
Stasiun Gubeng; primo Oktober 2007
Teringat Siwalan Zawawi
“Tuan, penyair?”
“Bukan. Saya cuma penjual siwalan
yang airnya tak ‘kan membasuh
dahaga kerongkongmu.
Air siwalan saya
hanya mampu mengguyur hatimu.”
“Tapi, sekarang, saya haus Tuan”
“Maka bermohonlah pada pencipta
siwalan itu;
Tuhanku,
Muhammadkanlah kerongkongku.
Puisikanlah hausku ini.”
Stasiun Gubeng; Ramadhan 1428 H
dibubuhkan denyya ketika 02.22 0 tanggapan